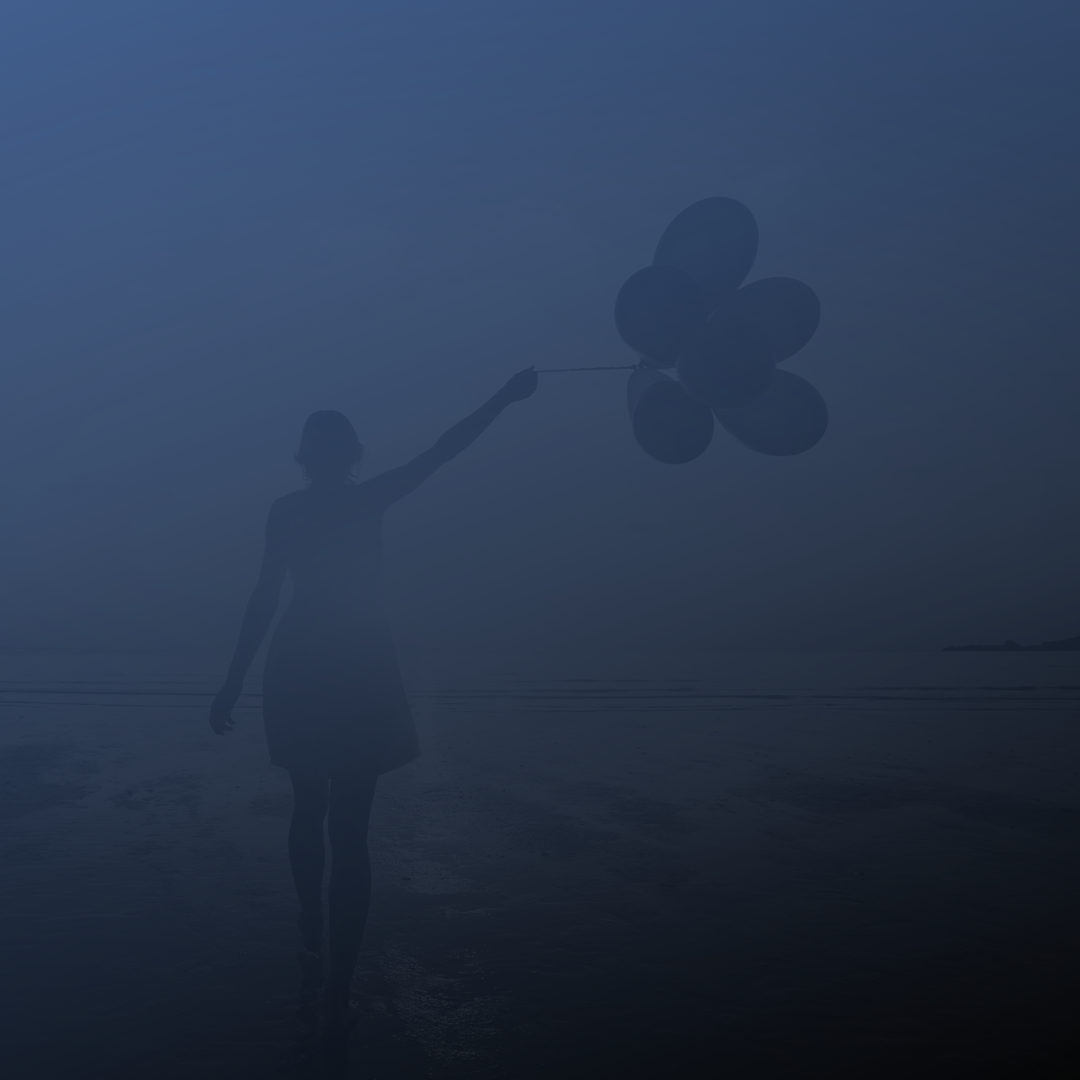
Self-Diagnose dan Psychobabble: Ketika Konten Psikologi Populer Membuat Kita Mudah Menyimpulkan
Oleh: Patrick Wijaya dan Azzahra Amanda, S. Psi
Dalam beberapa tahun terakhir, pembahasan mengenai kesehatan mental dan psikologi semakin sering muncul di ruang publik, terutama di media sosial. Di satu sisi, tren ini membantu masyarakat menyadari kesehatan mental dan mengurangi stigma negatif mengenai kesehatan mental itu sendiri. Namun, di sisi lain tren ini juga dapat memunculkan fenomena self-diagnosing atau perilaku mendiagnosa diri sendiri memiliki gangguan atau kondisi tertentu (Yoon dkk., 2024).
Belakangan, mulai terlihat fenomena baru yang serupa, tetapi dengan bentuk berbeda. Jika sebelumnya konten psikologi memicu orang mendiagnosa diri, kini berbagai istilah psikologi baik ilmiah maupun populer dipakai secara bebas sebagai bahan obrolan, bahkan kadang sebagai alat menyerang orang lain. Istilah seperti “high functioning depression”,”avoidant dan anxious attachment”, serta “narcissist”, digunakan tanpa pemahaman konteks ilmiah. Banyak pembuat konten menjual narasi psikologi dengan percaya diri, sementara penonton mudah terbawa sebab bahasanya terdengar logis dan merasa “relateable”.
Hasilnya: penyederhanaan dan generalisasi yang berlebihan.
Self-Diagnosing: Fenomena yang Membuka Jalan
Self-diagnosing muncul karena beberapa faktor, yaitu tingginya kepercayaan masyarakat pada informasi media sosial, informasi yang tidak terserap dengan baik menimbulkan mis-informasi, ekspektasi terhadap paparan konten yang berpengaruh pada perilaku atau tindakan selanjutnya terhadap situasi atau orang lain (self-fulfilling prophecy), serta intensitas menonton konten psikologi. Praktik tersebut dapat memicu dampak negatif seperti kecemasan berlebihan (cyberchondria), dan internalisasi (Gobel dkk., 2023).
Pop Psychology dan Psychobabble
Menurut Lack dan Rousseau (2022), pop psychology adalah konsep atau istilah yang tampak seperti penjelasan psikologis, tetapi tidak berbasis bukti ilmiah. Sementara psychobabble merujuk pada penggunaan jargon psikologi yang disampaikan secara keliru sehingga menyesatkan. Beberapa istilah yang cukup sering digunakan, seperti love language, inner child, dark psychology, empath, law of attraction, atau bahkan istilah diagnostik yang dibahas secara harfiah turut menjadi bahan konsumsi sehari-hari (Contreras, 2020).
Mengapa Psikologi Non-Ilmiah Digemari Publik?
Lack dan Rousseau (2022) menyebut empat alasan utama mengapa publik mudah percaya:
- Cognitive bias, otak cenderung memilih penjelasan yang sederhana dan mudah diterima meski tidak akurat.
- Confirmation bias, orang mencari informasi yang sesuai dengan keyakinan awal mereka.
- Availability heuristic, informasi yang mudah diingat dianggap lebih benar.
- Belief perseverance, mereka tetap percaya meski sudah terbantah secara ilmiah.
Henderson dkk. (2021) menambahkan adanya illusion of truth effect yang artinya semakin sering orang melihat sebuah informasi, semakin mereka menganggapnya benar. Maka algoritma media sosial yang seringkali menunjukan konten yang relevan bagi sang penonton akan memperkuat efek ini. Tidak heran pop psychology lebih digemari sebab penjelasannya ringkas dan instan.
Pathologizing: Ketika Perilaku Normal Dianggap Gangguan
Dalam Kamus APA (2018), pathology merujuk pada kondisi yang menyimpang dari keadaan sehat. Sutton (2020) menjelaskan bahwa pathologizing terjadi saat perilaku normal dianggap sebagai tanda gangguan. Padahal, reaksi manusia sangat dipengaruhi berbagai konteks, lalu durasi, intensitas, dan dampaknya (Eaton, 2023).
Salah satu contoh yang umum adalah pelabelan “narsis”. Seseorang yang merayakan pencapaian, tampil percaya diri, atau membagikan hal yang membuatnya bangga di media sosial kerap langsung disebut “narsis” atau bahkan “punya NPD”. Padahal, perilaku tersebut bisa sepenuhnya sesuai dengan konteks, misalnya bentuk ekspresi diri, kebutuhan afirmasi sosial yang wajar, atau sekadar gaya komunikasi personal. Label “narsis” dalam kasus ini tidak menunjukkan gangguan kepribadian, melainkan sekadar overgeneralization terhadap perilaku yang tampak.
Atau contoh lain, ketika seseorang menetapkan batasan dengan mengatakan “aku lagi butuh waktu sendiri”, perilaku tersebut kerap diberi label “avoidant attachment” atau “toxic”. Padahal, batasan tersebut dapat menjadi bentuk regulasi diri yang sehat dan sangat dipengaruhi oleh konteks emosional serta situasi interpersonalnya.
Jika orang awam dengan mudahnya menggunakan istilah tertentu, risikonya adalah labeling, yang mana individu mulai mengubah perilaku agar sesuai dengan label tersebut (Barmaki, 2017).
Prosesnya membentuk pola pathologizing :
konten yang mudah dipahami → generalisasi → “hipotesis” tentang diri/orang lain → konfirmasi selektif → labeling → keyakinan yang makin menguat (Eaton, 2023).
Dampak pada Persepsi Publik Terhadap Psikologi Ilmiah
Membludaknya konten pop psychology dan psychobabble memberi dampak nyata: patologisasi perilaku normal, kesalahpahaman terhadap istilah klinis, serta bias yang memperkuat misinformasi. Publik sering tidak membedakan psikologi ilmiah dari psikologi populer, sehingga penjelasan instan terasa lebih memuaskan. Fenomena ini juga dapat memperkuat stigma dan mengaburkan pemahaman masyarakat tentang psikologi sebagai ilmu yang berbasis bukti.
Di tengah banjir konten psikologi di media sosial, kita perlu berhenti menerima informasi secara mentah-mentah. Banyak istilah klinis yang dipopulerkan bukan oleh tenaga profesional, melainkan oleh kreator konten yang menyederhanakan konsep agar mudah viral. Dampaknya, label seperti “narsis,” “toxic,” atau “gaslighter” dipakai terlalu luas sampai kehilangan makna aslinya. Padahal, pathologizing others justru membuat kita gagal memahami persoalan sebenarnya apakah perilakunya memang problematik, atau hanya berbeda dari preferensi dan ekspektasi kita (Sutton, 2020; Eaton, 2023). Serahkan penegakan diagnosa kepada profesional seperti psikolog yang sudah jelas lebih ahli.
Berikut beberapa cara agar kamu tidak mudah melakukan patologisasi diri maupun kepada orang lain:
- Kritisi konten psikologi yang kamu lihat. Tanyakan: siapa sumbernya? Apakah ada rujukan ilmiah? Apakah istilahnya dipakai dengan tepat?
- Kenali batas penggunaan label. Istilah klinis dibuat untuk asesmen profesional, bukan untuk percakapan sehari-hari yang minim konteks.
- Pisahkan pengalaman subjektif dari klaim patologis. “Aku merasa tersakiti” adalah fakta; “dia narsis” adalah tuduhan yang butuh bukti dan kompetensi khusus.
- Ingat bahwa diagnosis bukan alat sosial. Label klinis memengaruhi cara kita memperlakukan seseorang; ketika digunakan sembarangan, label tersebut bisa merendahkan dan menstigma.
Dengan bersikap lebih kritis terhadap konten psikologi dan lebih berhati-hati menggunakan istilah klinis, kita membantu menciptakan ruang digital yang lebih akurat, lebih manusiawi, dan bebas dari miskonsepsi yang merugikan.Kunjungi para ahli jika ada pembahasan seputar kondisi mental yang ingin kamu konsultasikan pada tabula.id/psikolog atau tabula.id/konselor. Terdapat Psikolog Klinis, Psikolog Pasangan, hingga Psikolog Pendidikan.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi: 0819-1112-2232
Barmaki, R. (2017). On the origin of “labeling” theory in criminology: Frank Tannenbaum and the Chicago School of Sociology. Deviant Behavior, 40(2), 256–271. https://doi.org/10.1080/01639625.2017.1420491
Contreras, A. (2020, August 20). The trend of pop-diagnosing could become a threat. Medium. https://contrerasantonieta.medium.com/the-trend-of-pop-diagnosing-could-become-a-threat-63bbbbfc8a54
Eaton, C. (2023). Self-diagnosis & pathologizing normality during the information age (Master’s thesis). Murray State Theses and Dissertations, 298. https://digitalcommons.murraystate.edu/etd/298
Gobel, S. A. M., Lusiana, E., & Dida, S. (2023). Mental health promotion: Stop self-diagnosing through social media. Jurnal Promkes, 11(1), 71–81. https://doi.org/10.20473/jpk.V11.I1.2023.71-81
Henderson, E. L., Simons, D. J., & Barr, D. J. (2021). The trajectory of truth: A longitudinal study of the illusory truth effect. Journal of Cognition, 4(1), 1–23. https://doi.org/10.5334/joc.161
Lack, C. W., & Rousseau, J. (2022). Mental health, pop psychology, and the misunderstanding of clinical psychology. In G. J. G. Asmundson (Ed.), Comprehensive Clinical Psychology (2nd ed., Vol. 11, pp. 47–62). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-818697-8.00052-2
Sutton, J. (2020, November 4). What is pathologizing & overpathologizing in psychology? Positive Psychology. https://positivepsychology.com/pathologizing/
Yoon, D., Gil, S., Trumbull, J., & Lim, S. (2024). TikTok and the Prevalence of Self-Diagnoses and Psychological Disorders Among Teen Users. Journal of Student Research, 13(1). https://doi.org/10.47611/jsrhs.v13i1.6317